“Yang dibutuhkan seorang buta bukanlah seorang guru,
Melainkan diri mereka sendiri”
Hellen Adams Keller (1880-1968)
Pengantar
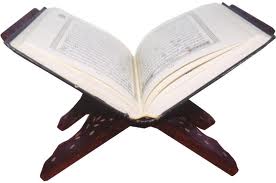 |
| Ilustrasi |
Meskipun kurang atau tidak ada perhatian akademis mengenai difabel, namun mitos mengenai dan terhadap penyandang difabel cukup hidup di masyarakat. Ada mitos di masyarakat bahwa (orang yang lahir) difabel adalah produk gagal. Mereka lahir sebelum sempurna untuk dilahirkan. Sebagian masyarakat mempercayai bahwa difabilitas yang dialami seseorang adalah akibat dari perbuatan yang melanggar norma social dan agama. Mitos lain menggambarkan difabel sebagai hukuman/kutukan yang patut diterima oleh seseorang atas kejahatan yang dilakukannya, baik langsung atau pun tidak langsung. Dalam agama Kristen, terdapat keyakinan bahwa mereka yang lumpuh dan buta yang disembuhkan oleh Yesus adalah orang yang penuh dosa. Mitos ini pula yang berkembang terhadap para penderita HIV/AIDS.
Ada dua kemungkinan, mengapa persoalan difabel tenggelam dalam limbo sejarah dan menjadi wilayah alla muffakar fihi (hal yang tak terpikirkan). Pertama; Islam memandang netral mengenai persoalan difabel ini. Tidak sebagaimana mitos-mitos di atas, Islam memandang bahwa kondisi difabel bukan anugerah dan apalagi kutukan Tuhan. Lebih dari itu, Islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh daripada melihat persoalan fisik seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti QS. al-Hujurat [49]: 11-13, an-Nahl [16]: 97, al-Isra’ [17]: 36 dan an-Nisa’ [4]: 124 dan Hadis, seperti HR. Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, tetapi Dia lebih melihat hati kalian. Dalam redaksi yang lain berdasarkan HR. Thabarani, Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian[3] dan hadis yang berbunyi: Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang mencintai kebaikan sekaligus senang mengerjakannya.[4] Dengan kata lain, Islam lebih memandang hal yang subtantif daripada hal-hal yang bersifat artificial serta lebih menekankan amal atau perbuatan baik. Karena itu ada yang menyebut bahwa Islam adalah agama amal atau kerja, bukan agama wacana atau oral.
Di samping alasan tersebut, melalui al-Qur’an juga Islam sangat melarang keras taskhir (menghina dan merendahkan) orang lain dengan alas an apa pun, seperti karena bentuknya, warna kulitnya, agamanya dan lain-lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan QS.al-Hujurat [49]: 11. Sebaliknya Islam sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai orang lebih dari yang ia terima, sebagaimana dikemukakan dalam QS. an-Nisa’ [4]: 86. Oleh karena itu, Allah pernah menegur Nabi Muhammad saw. ketika tak acuh dengan seorang difabel netra, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, seperti disebutkan dalam QS. ‘Abasa [80].
Kedua; ada yang menyatakan bahwa minimnya kajian mengenai difabel dalam khazanah pemikiran Islam klasik adalah karena minimnya pemikir Islam klasik dari kalangan difabel. Sejarah belum pernah mencatat adanya pemikir besar Islam, baik dalam bidang Akidah, Tasawuf, Filsafat, Fiqih, Tafsir, maupun Hadis yang berasal dari kalangan difabel,[5] meskipun di era modern kita menjumpai Thoha Husain (mantan Menteri Pendidikan Mesir dan seorang sejarawan dan Mahmud Ayoub (Guru Besar di Temple University Amerika dalam bidang Tafsir dan Comparatif Religion). Hal ini mirip seperti kajian mengenai perempuan. Agak sulit menemukan atau malah tidak ada pemikir dan penulis pemikiran Islam dari kalangan perempuan. Selama berabad-abad, dunia pemikiran Islam didominasi oleh kaum laki-laki “normal” (non-difabel).
Akibat ketiadaan kajian apalagi perspektif difabel ini mudah ditebak, yaitu adanya generalisasi dalam penyediaan kebutuhan dan fasilitas atau sarana bagi manusia. Semua manusia dianggap sama; dapat membaca buku dan berjalan dengan matanya, dapat mendengar dengan telinganya, dapat bicara dengan mulutnya, dapat berjalan; naik-turun dengan kakinya dan seterusnya. Karena itu tidak aneh kalau dalam Fiqih Islam misalnya ada kesan pengabaian terhadap kaum difabel ini, terutama dalam merumuskan beberapa ketentuan yang dikenal dengan syarat atau rukun. Kitab Fiqih tidak pernah menjelaskan secara detail tentang syarat sah berwudu bagi para difabel yang tidak memiliki lengan dan kaki misalnya. Kitab fiqih juga tidak pernah mengatur secara jelas bagaimana syarat sahnya ijab–qobul pernikahan bagi para difabel yang bisu–tuli. Bahkan pembahasan fiqih pun juga tidak kritis terhadap ribuan bangunan masjid yang tidak aksesibel bagi kaum difabel. Sepertinya fiqih hanya disusun untuk mereka yang “normal”. Ini artinya belum ada sensitifitas para fuqaha terhadap difabel. Kalaupun ada dalam pemikiran mereka, kelompok difabel dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang boleh mengambil rukhsah atau dispensasi, karena orang tersebut mengalami apa yang disebut dalam Fiqh sebagai dharurah (emergency), sehingga seorang difabel rungu tidak harus melakukan ijab-qabul sendiri. Ia –ketika menikah atau melakukan transaksi mu’amalah- boleh mewakilkan pada walinya.
Di Indonesia sendiri, yang jumlah kaum difabelnya -menurut data World Health Organization (WHO)- berjumlah 20 juta jiwa atau hampir 10% dari total populasi, yang terdiri dari tunanetra (blind), tunawicara (dumb), tunarungu (deaf), lumpuh (paralyze), dan jenis-jenis kecacatan lain baru memiliki undang-undang tentang penyandang cacat pada tahun 1997, yaitu UU No. 4 Tahun 1997. Dari jumlah itu, separo lebih adalah anak-anak yang tidak atau belum mendapat kesempatan menikmati pendidikan. Jumlah kaum tunanetra sendiri menurut data WHO tahun 2002 mencapai 1,5% dari total populasi, jauh lebih tinggi daripada negara-negara berkembang lain seperti Bangladesh (1%), India (0,7%), Thailand (0,3%). Sementara itu, masyarakat dunia, melalui UNESCO baru mendeklarasikan perhatian terhadap pendidikan kaum difabel ini pada tahun 1994 yang dikenal dengan Deklarasi Samalanca, Spanyol.
Pertanyaannya kemudian bagaimana sikap Islam sekarang? Apakah membiarkan penyandang difabel dan menyamakannya dengan yang lain? Apakah ada peluang untuk melihat persoalan difabel ini dalam literature tafsir. Kalau ada seperti apa? Bagaimana mufassir memposisikan difabel? Itulah beberapa pertanyaan yang menggelitik untuk dijawab.
Pengertian Difabel
Setiap tanggal 3 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Penyandang Cacat Internasional. Hal ini setelah sebelumnya pada tahun 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati konvensi untuk melindungi hak 650 juta manusia difabel sedunia. Dalam konvensi tersebut, melarang pembatasan kaum difabel dari hak pendidikan, pekerjaan dan politik. Lalu sebenarnya difabel itu apa atau siapa?
Istilah tersebut baru dipopulerkan oleh beberapa aktivis gerakan penyandang cacat di Indonesia pada 1998. Istilah tersebut merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris -meskipun bukan dalam bahasa Inggris sebenarnya- ‘differently abled people’ yang artinya orang yang berbeda kemampuan. Istilah tersebut diciptakan oleh orang Indonesia dan hanya digunakan di Indonesia. Sebab, kalau benar-benar bahasa Inggris, maka yang benar adalah difable. Sebaliknya, kata tersebut juga bukan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang benar.
Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut merupakan bentuk eufemisme (kata yang diperhalus). Istilah yang pertama kali digunakan adalah lame, kemudian diperhalus berturut-turut menjadi crippled, handicapped, disabled, dan terakhir differently-abled.[6] Penghalusan bahasa ini penting, karena istilah yang sering digunakan selama ini seperti cacat atau tuna terkesan berkonotasi negatif dan berpandangan sempit. Eufimisme juga terjadi dalam bahasa Indonesia, seperti gelandangan menjadi tuna wisma, pelacur menjadi pekerja seks komersil, dan sekarang menjadi wanita pekerja seks.
Namun, lebih dari sekedar penghalusan bahasa, difabel digunakan berdasarkan realitas bahwa setiap manusia diciptakan berbeda, sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan. setiap manusia diciptakan berbeda satu sama lain. Saya, kamu dan kita semua pasti beda. Tidak ada yang sama. Hanya masalah kemampuan yang berbeda. Bukan berarti mereka tidak mampu sama sekali. Mereka (para difable) dalam kenyataannya mampu melakukan apa yang biasa kita lakukan. Hanya saja dengan cara yang berbeda.
Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan berbeda-beda (different able) dengan rencana yang berbeda-beda juga. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurat [49]: 13. Karena itu alangkah baiknya jika perbedaan itu tidak ditafsirkan sebagai kesialan/kekurangan dengan istilah cacat.
Satu sisi, pengertian di atas bersifat umum dan cenderung terjebak pada pengertian generalis, sehingga tidak mengharuskan adanya “perlakuan khusus”, karena memang manusia, baik secara kodrati maupun social berbeda-beda atau beragam. Persoalannya hanya bagaimana setiap orang menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. Dalam posisi ini, semua manusia adalah setara. Karena itu, boleh jadi eufimisme ini justeru menjebak. Mungkin karena alasan inilah UU No. 4 Tahun 1997 masih menggunakan istilah penyandang cacat, meski dengan pemilahan, yaitu cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik dan mental. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU tersebut, penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Pada sisi lain, kedua definisi tersebut sama-sama lebih menekankan bukan hanya aspek jasadi-material manusia saja, tapi juga non jasadi. Karena itu di masyarakat dikenal istilah cacat moral dan social. Sementara itu, seorang difabel tertentu dalam kenyataan banyak mengukir prestasi.[7] Oleh karenanya, sangat tidak benar stigma negative terhadap mereka, seperti mereka lemah, tidak berdaya, dan lain-lain. Apa pun pengertian difabel, difable, disability, atau penyandang cacat, yang dimaksud dalam diskursus difabilitas sebenarnya bukan hanya yang bersifat fisik saja, tapi juga non fisik. Hal ini seperti tampak dalam macam-macam difabilitas. Lalu bagaimana menurut al-Qur’an atau tafsir? Apakah al-Qur’an merespon persoalan tersebut? Kalau betul merespon, apakah yang dimaksudkannya bersifat hakiki atau metafor saja. Inilah yang akan dicari referensinya dalam pembacaan al-Qur’an kini.
Macam-macam Difabel dan Karakteristiknya
Terdapat macam-macam difabel. Menurut PP No.7 Tahun 1991, minimal terdapat lima macam difabel, yaitu:
1.Difabel netra, yaitu seseorang yang mengalami gangguan daya penglihatan, baik berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Karakteristik difabel netra adalah:
a.Tidak mampu melihat,
Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter,
Kerusakan nyata pada kedua bola mata,
Sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan,
Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya,
Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/besisik/kering,
Peradangan hebat pada kedua bola mata,
Mata bergoyang terus.
2.Difabel rungu, yaitu seseorang yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Karakteristik difabel rungu adalah:
Tidak mampu mendengar,
Terlambat perkembangan bahasa,
Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi,
Kurang/tidak tanggap bila diajak bicara,
Ucapan kata tidak jelas,
Kualitas suara aneh/monoton,
Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar,
Banyak perhatian terhadap getaran,
Keluar nanah dari kedua telinga,
j.Terdapat kelainan organis telinga.
3.Difabel wicara, yaitu seorang yang mengalami atau tidak bisa bicara atau bisu. Karakteristiknya:
a.Gagap ketika menyampaikan sesuatu
b.Menggunakan bahasa isyarat
c.Biasanya tuli
4.Difabel daksa yaitu seseorang yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot). Karakteristiknya adalah:
Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh,
Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali),
Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa,
Terdapat cacat pada alat gerak,
Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam,
Kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal,
g.Hiperaktif/tidak dapat tenang.
5.Difabel grahita, yaitu seseorang yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun social. Karakteristiknya adalah:
Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar,
Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia,
Perkembangan bicara/bahasa terlambat,
Tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan (pandangan kosong),
Koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali),
f.Sering keluar ludah (cairan) dari mulut (ngiler).
6.Difabel laras, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain atau seseorang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Karakteristiknya adalah:
Bersikap membangkang,
Mudah terangsang emosinya,
Sering melakukan tindakan agresif,
Sering bertindak melanggar norma social/norma susila/hukum.
Potret Manusia dalam al-Qur’an dan Persoalan Difabilitas
Al-Qur’an bukan saja kitab suci yang diperuntukkan untuk manusia, tapi juga banyak berbicara mengenai manusia. Al-Qur’an menguraikan tentang manusia bukan saja dari sudut pandang statusnya, baik secara vertical maupun horizontal, namun juga dari sisi proses “produksi” (penciptaannya) dan reprduksinya.
Untuk melihat bagaimana difabilitas dalam al-Qur’an, dua sudut pandang tersebut digunakan sebagai alat analisis. Setidaknya terdapat tiga kosa kata yang sering digunakan al-Qur’an untuk menunjuk manusia, yaitu basyar, insan atau al-insan dan an-nas. Pertama; basyar. Basyar dan absyar merupakan bentuk jama’ (plural) dari kata basyarah berarti permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat bertumbuhnya rambut. Dari pengertian tersebut al-Asfihani dan ibn Barzah mengartikan basyarah dengan kulit luar atau permukaan kulit. Oleh karena itu kata muba>syarah diartikan banyak ulama fiqh dengan mula>masah artinya persentuhan kulit. Bagi mayoritas ulama fiqh, salah satu yang membatalkan wudhu adalah persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dewasa. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengartikan mubasyarah dengan al-wat’u atau al-jima>’ artinya persetubuhan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 178. Sehingga bagi sebagian kecil ulama fiqh ini, wudhu baru batal bila terjadi persetubuhan. Kalau hanya sekedar bersentuhan atau menempel, tidak membatalkan.
Manusia disebut basyar karena kulitnya yang tampak, tidak tertutup oleh rambut atau bulu. Hanya sebagian anggota tubuh saja yang tertutup rambut. Hal ini berbeda dengan hewan yang kulitnya tertutup oleh rambut atau bulu.[8] Dari makna tersebut, al-Qur’an memakai kata basyar untuk menunjuk manusia sebagai makhluk biologis—baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda—yang biasa makan, minum, berhubungan seks, beraktivitas di pasar, dan lain-lain.[9]. Basyar adalah manusia seperti yang kita kenal memiliki bangun tubuh yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama, ada di alam ini yang meruang dan mewaktu dan terikat dengan hukum alam. Proses alamiah dan faktor-faktor biologisnya, manusia terlahir sebagai anak yang lemah, tumbuh dengan empat kaki, berkembang berjalan dengan dua kaki dan tua dengan tiga kaki (yaitu tongkat), lalu lemah kembali dan akhirnya mati.[10] Para rasul, yang terekam dalam al-Qur’an juga berasal dari jenis manusia seperti kita (QS. Ibrahim [14]: 10-11). Mereka, termasuk Nabi Muhammad juga makan, bekerja, dan menikah, kecuali Isa (yang tidak menikah).
[1] Syuriah PCNU Kota Yogyakarta





+ komentar + 2 komentar
Assalamualaikum?
Saya Rahayu Triandari Putri, Mahasiswa Akhir di Ilmu Alquran Tafsir UIN Raden Fatah Palembang, kebetulan skripsi saya mengenai eksistensi disabilitas dalam Alquran..
Karena keterbatasan referensi dikota saya maka Saya memerlukan rujukan dan referensi dari post yang penulis sampaikan diatas.
Jika berkenan membantu, bisakah penulis menghubungi saya di rahayutriandariputri@gmail.com
Syukron katsiroon...
Wassalamualaikum
Terimakasih, sangat bermanfaat